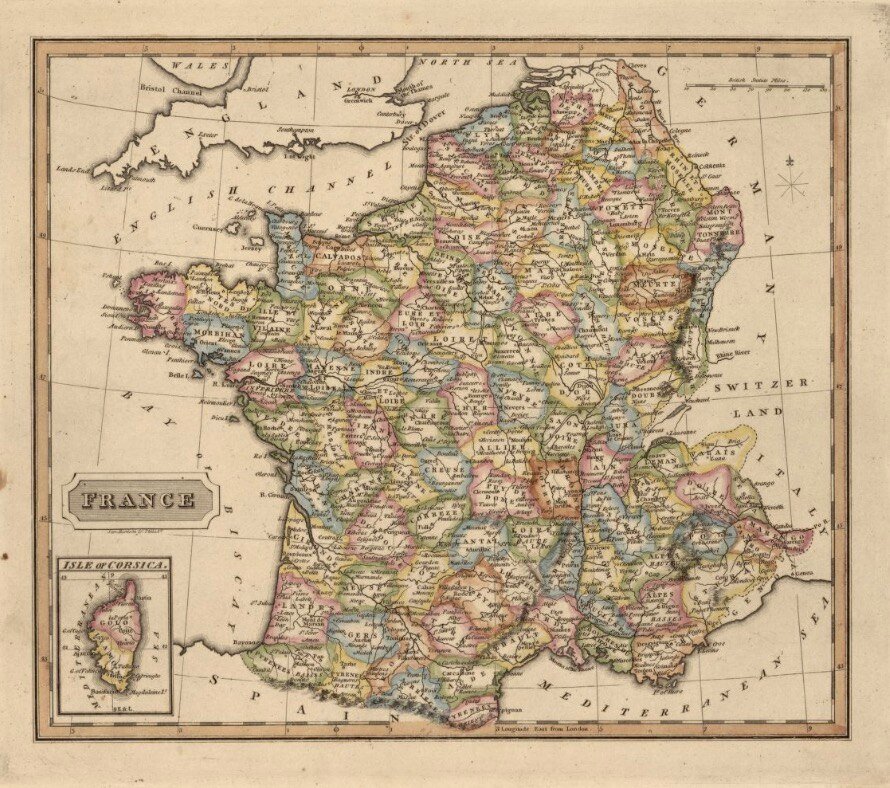
Suatu pagi, pertengahan tahun 2002, di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh. Syukurdi Mukhlis, mahasiswa IAIN Ar Raniry, terbangun dari lelap tidurnya di kamar hotel mewah tersebut. Dia sering berkunjung ke Kuala Tripa karena temannya, Amdy Hamdani, menjadi salah satu Juru Runding dari Gerakan Aceh Merdeka. Pada proses Damai Menuju Dialog yang difasilitasi oleh Henry Dunant Centre
Pagi itu, Syukurdi melihat Amdy Hamdani, bersama Teuku Kamaruzzaman, yang biasa disapa Ampon Man, sudah berpenampilan necis. Lengkap dengan Jas, juga dasi. Lalu dia bertanya kepada Hamdani ‘mau kemana bang?’ Dengan santai, yang ditanya menjawab ‘Mau ke Polda, untuk laporan. Sekarang lagi tunggu teman-teman dari LBH untuk mendampingi ke sana’.
Memang saat itu, Amdy Hamdani, Ampon Man, bersama juru runding GAM yang lain, seperti Usman Lampoh Awe, diwajibkan lapor secara rutin ke Polda Ace. Hal ini terjadi akibat pasang surut-nya dialog RI-GAM setelah berubahnya konstalasi politik nasional, pasca jatuhnya Gus Dur.
Lalu, tanpa beban, syukurdi pun bertanya ‘lho, ke Polda kok pakek dasi segala?’
Mendengar pertanyaan itu, hamdani pun mendelik, tanpa melepaskan tangan dari dasinya. Dia pun berkata, tentu dengan nada yang patriotik ‘Yang datang ini negara!’.
Mendengar jawaban demikian, Syukurdi pun manggut-manggut saja, karena tidak mengerti. Ampon Man, yang memang satu kamar dengan Hamdani di Hotel Kuala Tripa, hanya tersenyum saja melihat dialog ringkas tersebut.
Cerita ini saya dapatkan langsung dari Syukurdi Mukhlis, dan ketika saya konfirmasi langsung kepada Amdy Hamdani, dia pun membenarkan. Saya bertanya, kenapa muncul jawaban demikian. Mengapa saat itu berfikir, yang hadir ke Polda untuk wajib lapor adalah wakil sebuah negara berdaulat?
Jawabannya menurut saya menarik. Karena kesadaran itu dia dapat dari sebuah pengalamannya yang berkesan, yaitu ketika dia bertemu dengan Hasan Tiro di Swedia.
‘Saya dan Ampon Man pernah diusir oleh Tgk. Hasan Tiro dari sebuah jamuan makan malam di kediamannya di Swedia, hanya gara-gara kami tidak memakai jas dan dasi. Saat itu kami hanya memakai kaos. Malam itu suasana menjadi tegang, Tgk. Hasan, yang saat itu juga ditemani oleh Doto Zaini dan Mentroe Malek, tidak mau memulai makan malam, kalau kami masih ada di sana. Bahkan sampai mengetuk-ngetuk sendok ke piring, sebagai ekspresi kejengkelannya. Dan tidak ada satu pun di meja itu yang berani memulai untuk mengawali makan malam tersebut’.
Dalam refleksinya atas peristiwa itu, Hamdani mengatakan bahwa dia mendapatkan sesuatu dari Hasan Tiro, bahwa Aceh tidak sekedar hal yang besar-besar saja, namun juga pada style dan adab. Kasus yang makan malam itu menjelaskan dengan gamblang. ‘Tanjoe beu lagee Inggreh’ (Kita harus seperti Inggris), kata Hasan Tiro kepada Amdy Hamdani.
Perasaan bahwa Aceh merupakan bagian dari komunitas global dan selalu saja berfikir untuk bersanding dengan negara besar di luarnya, merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Bahkan hal itu ditunjukkan dengan bayangan bahwa Aceh dapat sejajar dengan negara lain, bukan provinsi lain!
Kita pula tidak pernah lupa bagaimana calon dari Partai Aceh, Zaini dan Mualem dalam satu janji kampanye nya, hendak membawa Aceh sejajar dengan Singapura dan Brunei Darussalam, bahkan malah bukan hendak mensejajarkan dengan Medan atau-pun Jakarta!
Bahkan dalam satu kesempatan, hal ini perlu saya ceritakan karena sangat unik, sebab mengambarkan bagaimana cara orang Aceh membayangkan dirinya dalam susunan masyarakat dunia. Hal ini saya dapatkan ketika berlangsungnya peluncuran buku Demokrasi: Pergeseran Nilai dari Ideologis ke Pragmatis terbitan Aceh Institute. Kebetulan saya menjadi moderator pada acara tersebut dan melihat seorang peserta berbicara dengan lugasnya.
Menurutnya, Aceh harus melihat bahwa demokrasi tidak hanya melulu dalam praktek liberal sebagaimana yang dipraktekkan di negara Barat, namun juga ada pilihan lain seperti demokrasi yang dipraktekkan di negara kesejahteraan, atau juga seperti yang diberlakukan di negara-negara komunis.
Bagi saya, yang berkesan adalah cara peserta itu memberikan pendapat akan hal tersebut tanpa beban sama sekali, dengan kenyataan bahwa Aceh hanya salah satu provinsi di dalam dekapan hangat Republik Indonesia.
Peserta tersebut, barangkali di luar kesadarannya, tidak perlu mengambil contoh demokrasi lokal di provinsi lain yang juga menyimpan keunikan tersendiri. Kita ambil contoh saja seperti di Yogyakarta dengan posisi Raja Jawa, atau DKI Jakarta yang rakyat hanya memilih Gubernur-nya secara langsung, sedangkan Walikota ditunjuk oleh Gubernur yang terpilih. Sebab baginya, begitu juga dengan Amdy Hamdani, karena memilik kesadaran yang terendap jauh, bahwa Aceh merupakan entitas besar layaknya sebuah ‘negara’. Sehingga tidak dapat ditolak ada perasaan ‘tidak ikhlas’ bahwa secara politik, kini Aceh hanyalah menjadi sebuah provinsi.
Saya mencoba melacak darimana imajinasi seperti itu muncul. Ada dua hal yang saya temukan, pertama adalah persentuhan Aceh dengan dunia di luarnya secara intens, diantaranya melalui gagasan Dunia melayu Raya, menyambut kedatangan Jepang dalam Perang Asia Pasifik, peran PUSA sebagai organisasi yang memobilisasi kelompok inteligensia Aceh periode awal, MoU Helsinki, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tsunami Aceh, dan kini munculnya kelompok terdidik baru yg sedang belajar di luar negeri, baik itu Amerika, Eropa, Tiongkok, Turki, Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dan yang menariknya, pengalaman mereka terhadap negara yang mereka sedang kunjungi itu, dapat kita ikuti secara rutin melalui citizen reporter di Harian Serambi Indonesia.
Kedua, hasil konstruksi sejarah Aceh, baik oleh sarjana asing maupun oleh penulis Aceh sendiri. Sarjana asing yang saya anggap ‘bertanggung jawab adalah Zentgraf, Paul van’t Veer, Dennis Lombardr dan Anthony Reid. Sedangkan dari penulis Aceh, peran beberapa nama patut dipertimbangkan, seperti Ali Hasjmy,HM. Zainuddin, Mohd. Said — nama ini, walau bukan dari Aceh tapi memiki peran besar dengan karya monumentalnya Aceh Sepanjang Abad. Juga tidak dilupakan peranan Ismail Jacub, Ibrahim Alfian dan Abu Bakar Atjeh.
Tema-tema dari penulis di atas pun seputaran perang Aceh, Revolusi Sosial, Hikayat Perang Sabil, merebut Selat Maka, Kejayaan Aceh Darussalam di Masa Iskandar Muda, kebesaran kepahlawanan Aceh seperti Tgk. Chiek di Tiro, hubungan kerajaan Aceh dengan imperium besar seperti Usmaniah dan Kerajaan Tiongkok.
Oleh karena itu, izinkan saya menguraikannya, satu persatu penyebab imajinasi itu selalu muncul dari generasi ke generasi. Diawali dari munculnya gagasan Dunia Melayu Raya, yang digagas oleh Ali Hasjmy.
***
Kiranya, penting memahami situasi politik Indonesia di awal 1990-an, untuk kemudian menjawab tentang pilihan politik kebudayaan Aceh dalam setting waktu tersebut. Yaitu bagaimana pertumbuhan kelas menengah musim di Indonesia (tepatnya di pusat kekuasaan Indonesia di Jawa) memberikan pengaruh besar terhadap relasi dan pewacanaan secara politik.
Dalam konteks sosiologis, intelektual muslim baru, yang kemudian mewarnai pewacanaan relasi Islam dan negara adalah dari kelas menengah. Sesuatu hal yang menjadi konskuensi logis dari stabilnya pembangunan ekonomi Orde Baru.
Dinamika tersebut melalui pembacaan Robison, menemukan bahwa kelompok kelas menengah itu, kemudian oleh rezim Orde Baru, digunakan untuk menopang pemerintahannya agar menjadi kuat dan saling memberikan dukungan untuk mempertahankan posisi politiknya.
Kelas menengah juga memiliki hubungan dengan proses demokratisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Anders Uhlin, bahwa baginya dengan adanya kelas menengah maka akan mendorong tumbuhnya partispasi politik yang tentu akan merangsang lahirnya proses demokratisasi (Edward Aspinall, 2005). Tesis yang serupa juga dikatakan oleh Huntington, bahwa khas kelompok kelas menengah di negara berkembang adalah tumbuh menjadi pendukung demokrasi (Anders Uhlin, 1997).
Hubungan antara kelompok kelas menengah dan demokrasi di Indonesia, dapat kita lihat ketika kelompok tersebut kemudian berhasil mendorong reformasi, setelah sebelumnya diawali dengan proses mobilitas vertikal yang cepat. Salah satu bagian dari kelas menengah adalah kelompok muslim yang dulunya terpinggirkan, namun karena melakukan politik kebudayaan, maka berhasil tumbuh menjadi kelompok menengah di Indonesia.
Bangkitnya kelas menengah dari kelompok muslim ini dapat dikatakan karena didorong oleh akses ke dunia pendidikan yang tinggi, sehingga kemudian dapat mempengaruhi sektor-sektor lain seperti ekonomi, politik dan birokrasi.
Bentuk lain yang dapat kita lihat adalah dengan mendorong gerakan Islam kultural melalui organisasi Islam, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan juga mendirikan Bank Muammalat pada awal 1990-an. Kedua hal itu, adalah keberhasilan atas apa yang dilakukan oleh intelektual muslim baru yang lahir pada awal Orde Baru. Intelektual muslim baru ini mencoba memberikan sintesa baru atas situasi politik dan sosial dalam hubungan Islam dan negara. Dan melalui ICMI-lah upaya menunjukkan bahwa hubungan yang penuh kecurigaan oleh rezim ini pada masa-masa awal telah terselesaikan.
ICMI dapat juga dikatakan sebagai seleberasi puncak dari Islam kultural. sekaligus untuk menciptakan keseimbangan politik terhadap kekuatan militer dan yang pro-demokrasi yang mulai menjadi tantangan bagi rezimnya (Robert W. Hefner, 2000).
Kehadiran ICMI dijelaskan oleh Nurcholis Madjid sebagai kekuatan yang hadir ketika Indonesia memasuki situasi sosial politik dengan perimbangan kekuatan baru, setelah berakhirnya era politik warisan kolonial dan mulai memasuki isu-isu seperti demokrasi, keterbukaan dan keadilan (Ahmad Gaus, 2010).
Lalu bila demikian, dimana letak Aceh dalam stabilitas politik Indonesia di awal tahun 1990-an?
Aceh menjadi provinsi seperti biasa. Apalagi dengan hilangnya dominasi PPP dalam jagat politik Aceh, telah menyisakan narasi tentang nasib buram Islam politik di Aceh. Terlebih semakin penyangga Islam politik oleh tokoh-tokoh PUSA semakin terpinggirkan ketika alat negara, seperti militer dan birokrasi, menjadi semakin kuat.
Kemudian,p ertumbuhan kelas menengah di pusaran Indonesia tidak juga mendorong Aceh untuk melakukan konstruksi wacana secara genuine, seperti yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Aceh menjadi biasa karena kemudian hanya meneruskan dinamika yang sedang berlangsung di pusaran kekuasaan, tanpa menawarkan keunikan apapun.
Sampai kemudian Ali Hasjmy mendorong sebuah gerakan kebudayaan yang disebut oleh Ali Hasjmy sebagaiDunia Melayu Raya
Dunia Melayu Raya adalah sebuah gerakan yang akan mengintegrasikan kebudayaan di dalam kawasan ASEAN melalui persamaann bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Singapura, Thailand dengan bahasa Indonesia, dan bahkan, klaim Hasjmy, gerakan kebudayaan ini akan semakin menguatkan peran ASEAN (Serambi Indonesia 1992).
Gerakan kebudayaan ini sebenarnya berkelindan juga dengan keberadaan Lembaga Kebudayaan Aceh (LAKA). Sebuah lembaga kebudayaan yang bekerja untuk memproduksi pengetahuan pada tema-tema kebudayaan, humaniora, sastra dan sejarah. LAKA ini sendiri lahir dari rekomendasi Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan di Takengon 1986, yang dihadiri dari berbagai utusan dalam dan luar negeri, sehingga LAKA diharapkan kehadirannya dapat membina kembali adat dan kebudayaan Nusantara (Ali Hasjmy, 1995).
Dalam konteks dunia Melayu Raya, LAKA diharapkan dapat menjadi jembatan dunia Melayu di atas Selat Melaka, Selat Jawa dan Sunda, Selat Bali, Selat Nusantara Barat dan Timur, Selat Kalimntan, Selat Ambon, Selat Teluk Cendrawasih dan di atas laut yang membentang antara Sulawesi dan Filipina Selatan.
Upaya LAKA untuk menjembatani hubungan Aceh dan Dunia Melayu salah satunya dengan penerbitan sebuah pamflet yang berjudul Aceh dan Pahang, yang memuat tiga buah artikel mengenai Putri Pahang dan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani sebagai simbol persaudaraan Aceh dan Pahang, serta hubungan antara Aceh, Perak, Bugis dan Pahang. Keberadaan pamphlet tersebut menjelaskan bagaimana upaya untuk menarik garis kesamaan antara Aceh dan Dunia Melayu melalui eksplorasi sejarah dan kebudayaan.
Dalam catatan penutup dari dua tulisan ini, gagasan tentang Dunia Melayu Raya adalah sebuah respon intelektuil yang jernih dalam melihat kondisi Aceh yang semakin biasa dan semakin hilangnya keberadaan imajinasi sebagai entitas global. Sesuatu hal yang sedang berlangsung secara terang benderang akhir-akhir ini.
Yang dulunya memiliki imajinasi besar dan melampaui sekat-sekat provinsi, kini malah menjadi semakin mengkerut. Maka perlu dikemudian hari, melalui pertumbuhan generasi baru Aceh yang lebih terdidik, untuk mengakumulasi kesadaran tentang provinsi yang rasa “negara”.
Yogyakarta, 9 Juni 2022
